Integritas, Pilar Utama Menuju Indonesia Emas

oleh : Dede Farhan Aulawi
naraga.id — Integritas kerap digaungkan dalam berbagai forum sebagai kunci utama menuju masa depan Indonesia yang maju dan berkeadaban. Namun, di tengah semangat membangun Indonesia Emas 2045, integritas justru sering terjebak sebagai jargon tanpa makna nyata dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setiap tahun, saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada pentingnya integritas. Kata ini sering diangkat dalam seminar, pelatihan etika, hingga forum birokrasi. Meski terdengar ideal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi nilai ini masih jauh dari harapan.
Apa Itu Integritas?
Secara umum, integritas merujuk pada kesatuan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Ia mencakup kejujuran, konsistensi, serta komitmen moral terhadap kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas didefinisikan sebagai “mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan.”
Penulis dan konsultan kepemimpinan Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, menyebut integritas sebagai “the value we place on ourselves”, atau nilai yang kita tanamkan pada diri sendiri—bukan sekadar citra di hadapan publik.
Fenomena “Integritas Kelompok”
Meski secara ideal integritas mengakar pada kebenaran universal dan kepentingan rakyat, realitas politik hari ini menunjukkan pergeseran makna yang mengkhawatirkan. Dalam dunia kekuasaan, loyalitas kepada kelompok seringkali lebih dihargai dibanding kesetiaan pada nilai dan konstitusi.
Fenomena ini melahirkan istilah “integritas kelompok”—sebuah orientasi yang menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan publik. Seorang dengan “integritas kelompok” akan setia pada agenda kelompok, bahkan jika harus mengorbankan nilai moral atau menutupi pelanggaran.
Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 mencatat bahwa sebagian besar pelaku korupsi merupakan kader partai politik atau orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Namun, sangat jarang ditemukan pengungkapan kasus secara menyeluruh. Sering kali, satu orang memilih diam demi menjaga nama kelompoknya.
Dampak Sistemik
Distorsi terhadap makna integritas ini sangat berbahaya. Ketika kejujuran hanya berlaku dalam lingkup kelompok, maka ruang publik kehilangan rujukan moral. Politik menjadi transaksional. Integritas berubah dari prinsip menjadi alat tukar kekuasaan.
Jika tren ini terus berlangsung, Indonesia bukan hanya menghadapi krisis korupsi, tetapi juga krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan. Ketika kesetiaan kepada kelompok lebih dijunjung daripada kesetiaan kepada negara, maka moralitas publik terancam tergerus secara sistemik.
Mengembalikan Arah
Pertanyaan besar pun muncul: ke mana arah integritas bangsa ini ke depan? Apakah masih ada ruang bagi pemimpin yang jujur, yang lebih mendahulukan bangsa ketimbang loyalitas sempit?
Jawaban dari pertanyaan tersebut bergantung pada seberapa kuat komitmen bersama untuk menempatkan integritas kembali pada tempatnya—yakni sebagai kompas moral, bukan sekadar slogan politik.
Momentum Hari Anti Korupsi harus dijadikan refleksi nasional. Apakah sistem politik dan pendidikan telah membentuk pribadi-pribadi yang menjunjung kejujuran? Apakah masyarakat lebih menghargai prinsip dibanding pencitraan?
Jika tidak, bangsa ini berisiko melahirkan generasi yang unggul dalam membangun citra, namun rapuh dalam nilai dan prinsip.
Menuju Indonesia Emas
Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, integritas harus dijadikan fondasi dalam setiap aspek kehidupan. Ia bukan sekadar jargon, melainkan energi moral yang menggerakkan perubahan. Menjaga integritas berarti menjaga arah masa depan bangsa—bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

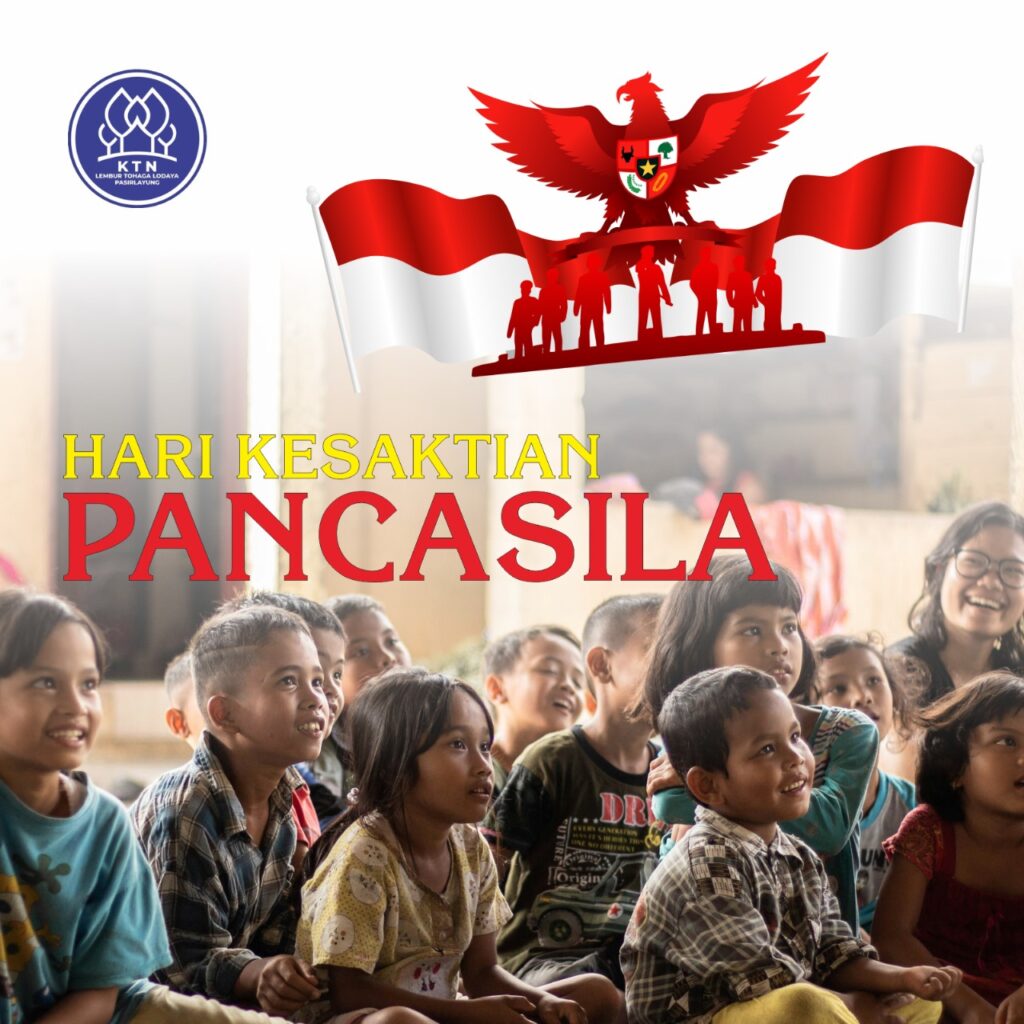






Tinggalkan Balasan